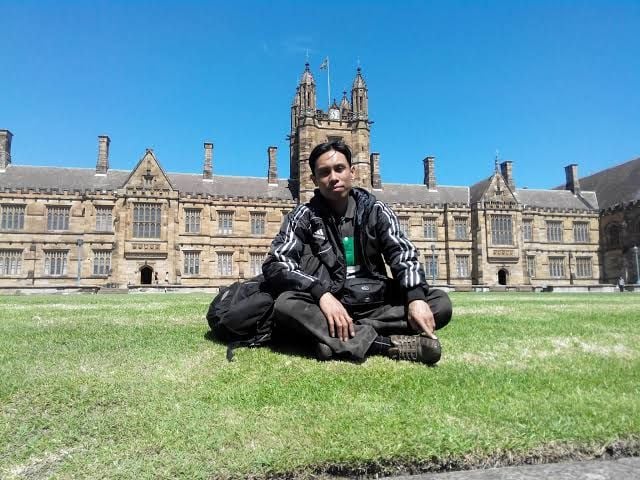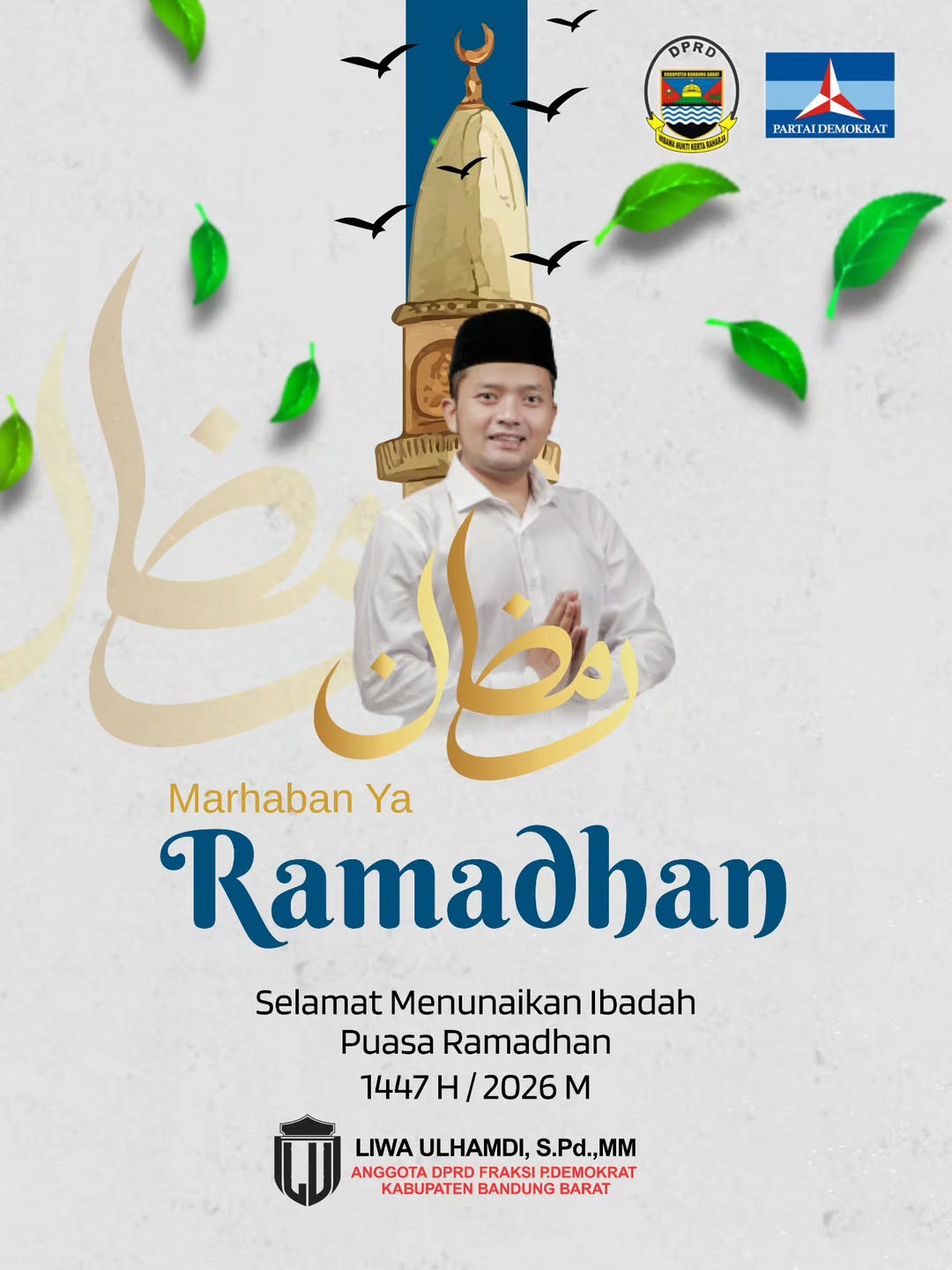BANDUNG-GMN,- Pendidikan sejatinya bukan sekadar proses mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi proses memanusiakan manusia.
Itulah hakikat pendidikan sebagaimana ditekankan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, yang menyebutkan bahwa pendidikan harus berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya manusia yang beradab, cerdas, dan bermoral.
Dalam konsep Tri Pusat Pendidikan, Ki Hajar menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan adalah tugas bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya harus bersinergi agar proses pendidikan berlangsung utuh dan bermakna.
Namun, dalam realitas hari ini, sinergi itu sering kali rapuh. Pendidikan menjadi beban salah satu pihak terutama guru sementara peran orang tua dan masyarakat tidak seimbang.
Akibatnya, tugas guru menjadi sangat berat, bahkan kadang membuatnya berada dalam posisi serba salah: ketika terlalu lembut, murid menjadi tidak disiplin; ketika tegas, guru justru dianggap melanggar hak anak. Inilah potret kompleks dunia pendidikan kita hari ini.
Keluarga: Sekolah Pertama yang Semakin Terlupakan
Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama. Di rumah, anak pertama kali belajar berbicara, bersikap, menghargai, dan berinteraksi. Nilai-nilai seperti sopan santun, tanggung jawab, dan empati seharusnya ditanamkan di rumah sebelum anak mengenal dunia luar. Pola asuh orang tua sangat menentukan karakter anak.
Sayangnya, di era modern ini, banyak orang tua yang abai terhadap peran pendidikannya. Kesibukan bekerja, gaya hidup konsumtif, dan kemudahan teknologi membuat sebagian orang tua menyerahkan seluruh tanggung jawab pendidikan kepada sekolah. Anak lebih banyak “diasuh” oleh gawai dan media sosial, ketimbang oleh orang tuanya sendiri. Padahal, pola asuh yang kurang bijak di rumah menjadi akar dari banyak masalah perilaku di sekolah: anak sulit diatur, tidak sopan, bahkan kehilangan empati terhadap orang lain.
Lebih ironis lagi, ketika terjadi masalah di sekolah, sebagian orang tua justru memposisikan diri sebagai pembela anak tanpa mau mendengarkan versi guru.
Ketika anak dihukum atau ditegur karena melanggar aturan, orang tua sering kali langsung bereaksi emosional. Bukannya berdialog, mereka malah membawa persoalan itu ke media sosial atau bahkan ke pihak berwajib.
Fenomena ini semakin mengikis kepercayaan antara sekolah dan keluarga, padahal keduanya seharusnya menjadi mitra sejajar dalam mendidik anak.
Sekolah: Mitra Orang Tua yang Kini Kehilangan Wibawa
Sekolah merupakan lembaga formal yang berperan memperkuat dan melanjutkan pendidikan yang sudah ditanamkan keluarga.
Di sekolah, anak bukan hanya belajar berhitung dan membaca, tetapi juga belajar hidup dalam tatanan sosial yang lebih luas. Guru berperan sebagai pendidik, pembimbing, sekaligus teladan. Ia bukan hanya pengajar mata pelajaran, tetapi juga penanam nilai dan pembentuk karakter.
Namun, realitas hari ini menunjukkan bahwa wibawa sekolah dan guru semakin menurun. Banyak murid yang kehilangan rasa hormat kepada gurunya. Fenomena ini tidak muncul begitu saja; salah satunya merupakan dampak negatif dari perkembangan media sosial yang kerap menampilkan perilaku kurang sopan, budaya instan, dan sikap menentang otoritas tanpa dasar yang jelas. Ketika perilaku seperti itu dianggap lumrah oleh anak-anak, mereka pun membawa nilai-nilai itu ke lingkungan sekolah.
Guru kini menghadapi dilema besar: ketika berusaha menegakkan disiplin, ia sering kali dianggap melakukan kekerasan. Rasa takut guru untuk mendisiplinkan murid muncul karena khawatir dilaporkan melanggar hak anak.
Beberapa kasus bahkan berujung pada laporan hukum atau viral di media sosial, yang berakhir dengan tekanan publik tanpa proses yang proporsional. Alhasil, banyak guru menjadi gamang dan apatis — mereka memilih sekadar mengajar tanpa berani menegur murid yang melanggar aturan.
Padahal, pendidikan tanpa kedisiplinan ibarat menanam tanpa menyiram. Ilmu pengetahuan bisa disampaikan, tetapi karakter tidak akan terbentuk. Jika guru hanya berfokus pada penyampaian materi, tanpa menanamkan nilai, maka sekolah hanya akan melahirkan manusia yang cerdas secara akademis tetapi miskin moral.
Dilema Disiplin dan Tuduhan Kekerasan
Kedisiplinan dalam pendidikan sejatinya merupakan bentuk kasih sayang. Guru yang memberikan teguran, nasihat, bahkan sanksi ringan kepada murid yang melanggar aturan, sebenarnya sedang mendidik agar anak belajar bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, di tengah perubahan paradigma masyarakat, setiap bentuk teguran kini berpotensi dianggap sebagai kekerasan.
Padahal, sudah ada mekanisme yang jelas untuk menangani dugaan kekerasan di satuan pendidikan. Di setiap sekolah telah dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (TPPKSP).
Bahkan di level daerah pun ada Satgas PPKSP. Tim ini berfungsi menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan dengan pendekatan musyawarah, objektif, dan berkeadilan. Artinya, jika memang ada pelanggaran, dapat diselesaikan secara internal melalui jalur yang beradab, bukan dengan cara-cara emosional atau main viralkan di media sosial.
Selain itu, di sekolah juga ada komite sekolah yang seharusnya berfungsi sebagai jembatan antara orang tua dan pihak sekolah. Komite tidak hanya mengurusi urusan dana atau fasilitas, tetapi juga menjadi forum komunikasi dan mediasi ketika terjadi perbedaan pandangan.
Sayangnya, peran ini sering kali tidak berjalan efektif karena komite kurang berdaya atau tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang fungsi mediasi dalam dunia pendidikan.
Menegakkan Disiplin dengan Dialog dan Restitusi
Dalam konteks pendidikan yang memanusiakan manusia, pendekatan disiplin tidak lagi dimaknai sebagai hukuman, melainkan sebagai proses pembelajaran bagi murid untuk memperbaiki diri.
Jika ada murid yang melanggar aturan, maka yang dikedepankan oleh sekolah bukanlah hukuman fisik atau penyerangan verbal, melainkan dialog, disiplin positif, dan segitiga restitusi.
Melalui dialog edukatif, guru berusaha memahami alasan di balik perilaku murid. Guru bertanya, mendengar, dan mengajak murid merefleksikan tindakannya.
Pendekatan ini membantu murid menyadari kesalahannya tanpa merasa dipermalukan. Kesadaran itulah yang menjadi titik awal perubahan perilaku.
Disiplin positif menekankan bahwa setiap kesalahan adalah kesempatan belajar, bukan alasan untuk menghukum.
Guru membantu murid memikirkan konsekuensi dari tindakannya dan mengajak mereka mencari cara memperbaiki kesalahan tersebut. Sementara itu, segitiga restitusi menjadi langkah konkret dalam membangun tanggung jawab murid melalui tiga tahap:
- Menstabilkan identitas murid, agar mereka tidak merasa terancam dan siap untuk berpikir jernih.
- Memvalidasi tindakan murid, dengan memahami alasan di balik pelanggaran tanpa langsung menghakimi.
- Menanyakan solusi, yakni mengajak murid memikirkan apa yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki keadaan dan mengembalikan nilai yang dilanggar.
Dengan cara ini, murid tidak hanya patuh karena takut hukuman, tetapi karena memiliki kesadaran moral dari dalam diri. Disiplin positif menumbuhkan tanggung jawab, empati, dan kesadaran diri — nilai-nilai yang jauh lebih berharga daripada sekadar ketaatan formal.
Namun, tidak semua murid langsung berubah setelah diberi kesempatan berdialog. Jika murid masih mengulang kesalahan yang sama, langkah selanjutnya adalah berkomunikasi dengan orang tuanya.
Guru dan orang tua perlu duduk bersama mencari akar permasalahan dan solusi terbaik. Barangkali ada faktor keluarga, lingkungan, atau psikologis yang memengaruhi perilaku anak. Dengan keterlibatan orang tua, proses pendidikan menjadi lebih menyeluruh.
Mendidik karakter murid saat ini memang bukan hal yang mudah. Diperlukan kesabaran yang berlipat-lipat dari guru. Murid-murid hidup di tengah derasnya arus informasi dan budaya instan, sehingga mereka sering kali sulit fokus dan tidak tahan terhadap proses panjang.
Guru perlu memiliki hati yang luas, kemampuan reflektif, dan kesadaran bahwa setiap anak adalah pribadi yang unik dan sedang belajar menjadi manusia seutuhnya.
Fenomena Media Sosial dan Penghakiman Publik
Salah satu tantangan besar pendidikan masa kini adalah kekuatan media sosial. Di satu sisi, media sosial memberikan ruang kebebasan berekspresi dan mempercepat arus informasi.
Namun di sisi lain, ia juga menjadi arena penghakiman massal tanpa batas. Ketika ada kasus guru menegur atau menghukum murid, sebagian orang tua langsung curhat atau mengunggah video kejadian ke media sosial. Narasi yang dibangun pun cenderung sepihak, tanpa konfirmasi.
Begitu kasus viral, netizen pun bereaksi cepat. Mereka menghujat, menghakimi, bahkan menuntut agar guru dipecat tanpa mengetahui konteks sebenarnya. Tidak jarang pula kepala daerah ikut bereaksi berlebihan, mengeluarkan pernyataan keras seolah ingin menunjukkan kepedulian, tetapi justru memperkeruh suasana. Padahal, seorang pemimpin pendidikan seharusnya menjadi penengah, bukan pemantik polemik.
Dalam sistem birokrasi pemerintahan, guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki mekanisme pembinaan tersendiri. Ada Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin ASN yang mengatur bagaimana sanksi dijatuhkan jika terjadi pelanggaran.
Tidak bisa seorang kepala daerah atau pejabat publik begitu saja memecat guru tanpa proses klarifikasi dan pembinaan yang sesuai prosedur. Sikap reaktif semacam ini justru memperlemah semangat para pendidik dan menciptakan ketakutan kolektif di kalangan guru.
Ketika Guru Takut, Pendidikan Kehilangan Ruhnya
Guru adalah ujung tombak pendidikan. Jika mereka takut menjalankan perannya sebagai pendidik, maka pendidikan akan kehilangan ruhnya. Banyak guru hari ini memilih “aman” tidak menegur murid, tidak memberi sanksi, tidak menasihati secara tegas. Mereka hanya datang mengajar, menyampaikan materi, lalu pulang. Semua itu dilakukan untuk menghindari risiko tuduhan atau laporan yang bisa mencemarkan nama baik.
Namun, ketika guru berhenti mendidik dan hanya mengajar, maka pendidikan kehilangan maknanya. Guru bukan sekadar pengajar, tetapi pembentuk watak bangsa. Dalam tangannya, generasi masa depan ditempa.
Jika guru kehilangan keberanian untuk menegakkan nilai-nilai kedisiplinan dan moral, kita sedang mencetak generasi yang pintar tetapi rapuh, kritis tetapi tanpa arah moral.
Sikap apatis guru tentu bukan tanpa sebab. Mereka membutuhkan perlindungan hukum dan dukungan moral dari semua pihak: orang tua, masyarakat, hingga pemerintah daerah. Pendidikan tidak akan pernah berhasil jika guru dibiarkan berjuang sendiri dalam ketakutan dan keraguan.
Pentingnya Sinergi dan Komunikasi antara Sekolah dan Orang Tua
Pendidikan yang baik hanya bisa terwujud melalui sinergi antara sekolah dan orang tua. Orang tua harus memahami bahwa tugas mendidik bukan hanya tanggung jawab guru. Begitu pula sebaliknya, guru harus memahami latar belakang keluarga dan kondisi psikologis murid agar dapat mendidik dengan pendekatan yang tepat.
Salah satu kunci utama keberhasilan pendidikan karakter adalah komunikasi dan koordinasi. Ketika guru menghadapi kesulitan dalam mendisiplinkan murid, sebaiknya ada ruang dialog bersama orang tua.
Begitu pula, jika orang tua merasa ada ketidaksesuaian dalam perlakuan guru terhadap anak, hendaknya dikomunikasikan secara langsung dan terbuka. Musyawarah adalah jalan terbaik, bukan pengaduan emosional apalagi penyebaran isu di ruang publik digital.
Pendekatan non-litigasi (musyawarah) bukan berarti mengabaikan keadilan. Justru sebaliknya, ia menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan kekeluargaan di atas ego dan amarah.
Dengan duduk bersama, mendengarkan, dan memahami satu sama lain, maka solusi yang adil dan mendidik bisa ditemukan.
Menuju Pendidikan yang Memanusiakan
Jika kita kembali pada filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan sejatinya adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka tumbuh menjadi manusia yang merdeka merdeka pikirannya, merdeka jiwanya, dan merdeka tindakannya dalam batas tanggung jawab moral. Untuk mencapai cita-cita itu, pendidikan harus menjadi ruang yang aman, dialogis, dan berkeadilan.
Namun, keamanan dalam pendidikan bukan berarti menghapus ketegasan, dan keadilan bukan berarti membiarkan pelanggaran. Guru tetap harus mendidik dengan kasih, tetapi juga dengan wibawa. Anak tetap harus diberi ruang berekspresi, tetapi juga diajarkan batas-batas etika dan tanggung jawab.
Di sinilah pentingnya kolaborasi antara tiga pusat pendidikan: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Orang tua menjadi pondasi karakter; sekolah menjadi ruang penguatan moral dan pengetahuan; masyarakat menjadi cermin nilai dan perilaku sosial. Ketika ketiganya berjalan harmonis, maka pendidikan tidak hanya mencetak murid yang pandai, tetapi juga manusia yang beradab.
Mengembalikan Marwah Guru dan Kepercayaan Publik
Sudah saatnya semua pihak orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah mengembalikan marwah guru sebagai pendidik bangsa. Tidak ada guru yang ingin menyakiti muridnya; yang ada hanyalah guru yang berusaha mendidik dengan cara yang ia yakini benar, meski kadang belum sempurna.
Kita perlu kembali menumbuhkan budaya saling menghormati di lingkungan pendidikan. Jika terjadi kesalahpahaman, jangan langsung membawa ke ranah hukum atau media sosial.
Selesaikan dengan dialog dan musyawarah. Di sinilah nilai-nilai Pancasila, gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan menemukan maknanya dalam praktik nyata.
Pendidikan yang memanusiakan manusia tidak mungkin terwujud jika guru dibungkam oleh rasa takut, orang tua dibutakan oleh ego, dan masyarakat terjebak dalam penghakiman digital.
Hanya dengan kerja sama, empati, dan komunikasi yang tulus, kita bisa mengembalikan pendidikan pada hakikatnya: membangun manusia yang cerdas, berkarakter, dan berkepribadian luhur.